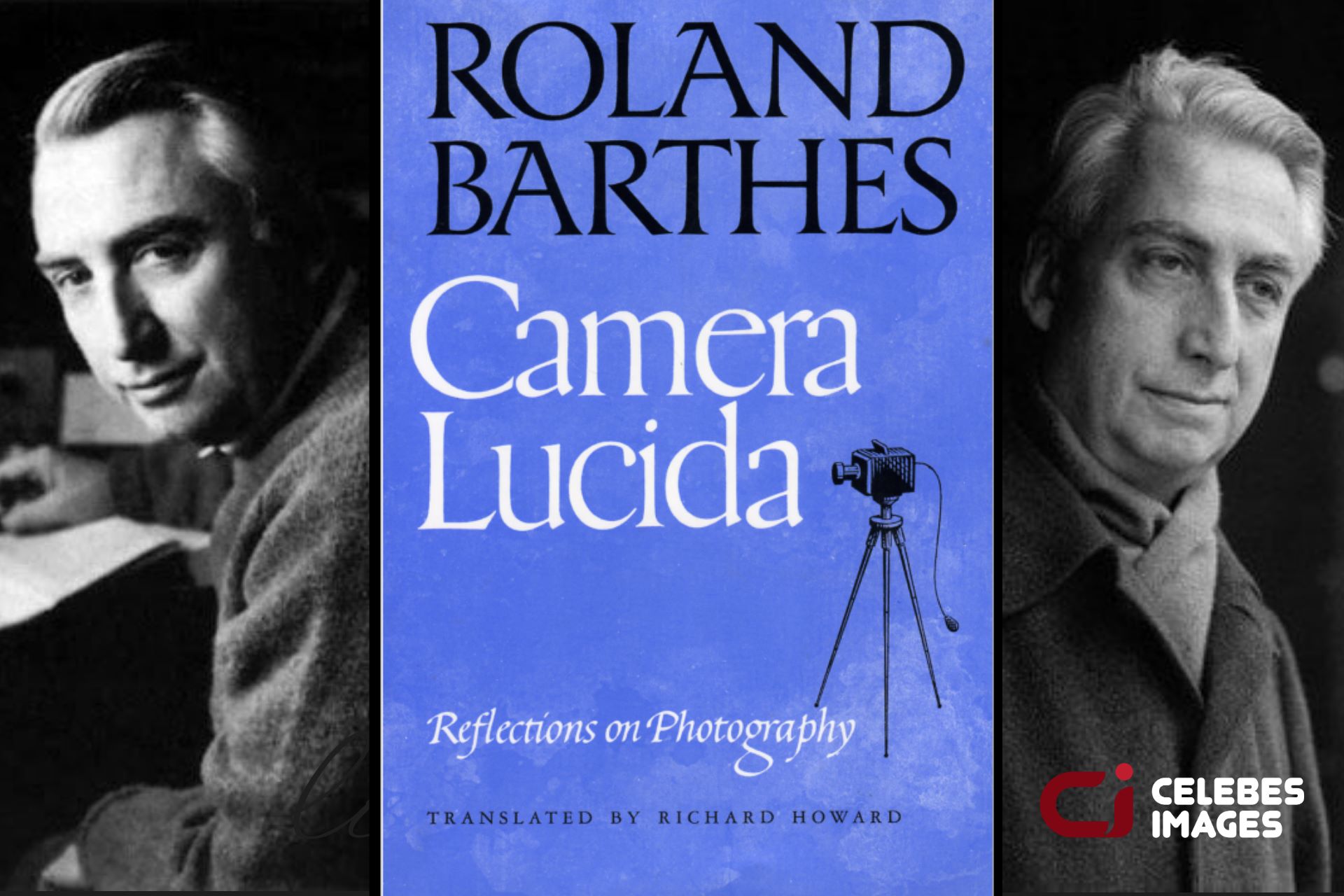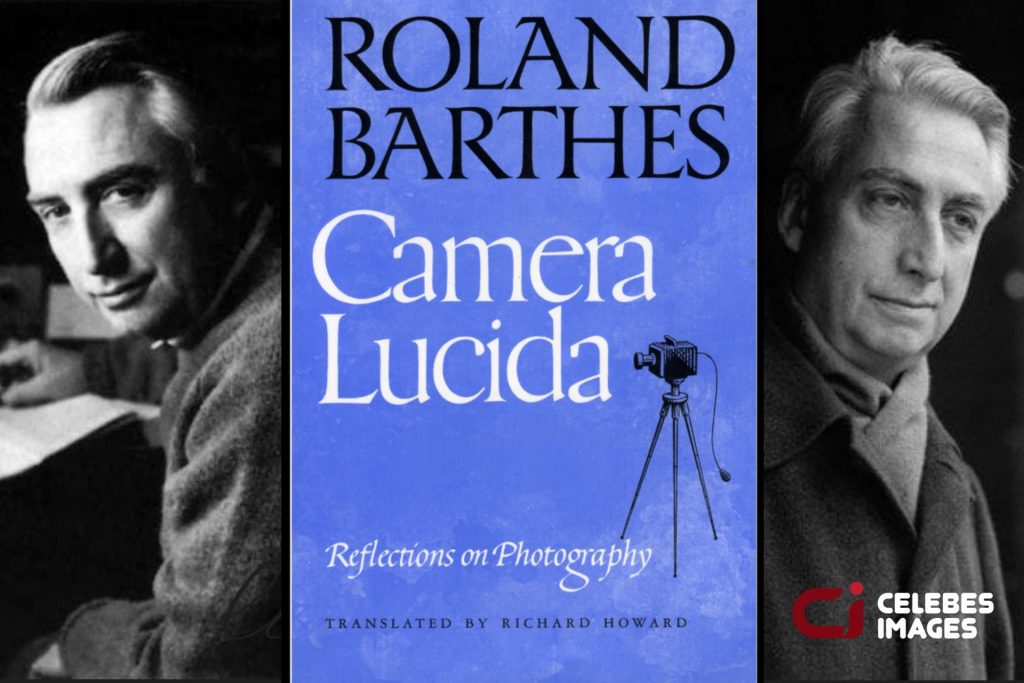
Bagian II Memasuki Gerbang Camera Lucida
Camera lucida, sebuah frasa yang dalam bahasa Latin berarti “ruang terang,” bukan sekadar judul bagi karya filsafat Roland Barthes; ia adalah jendela menuju renungan yang lebih dalam.
Dalam dunia optik, istilah ini merujuk pada sebuah alat dari abad ke-19, sebuah perangkat yang bagi para seniman kala itu menjadi semacam medium mistis.
Camera lucida, melalui prisma atau cermin memungkinkan seniman melihat dua dunia sekaligus: pemandangan yang ada di depan mata dan permukaan kertas tempat tangan mereka menari, menelusuri garis-garis yang hadir seakan-akan realitas itu sendiri telah bersatu dengan medium. Camera lucida menjadi titian di mana realitas dan imaji bertaut dalam harmoni.
Namun, Barthes mengangkat istilah ini ke dimensi metaforis yang lebih tinggi. Dalam buku Camera Lucida, ia tidak berbicara tentang alat optik, melainkan tentang lensa spiritual, yaitu suatu “ruang terang” di mana fotografi menjadi saksi bisu dari “keber-ada-an” yang telah berlalu, kehadiran yang tidak lagi ada.
Bagi Barthes, foto bukan sekadar gambar; ia adalah fragmen dari waktu yang membeku, sebuah bukti dari apa yang pernah nyata. Setiap foto memikul jejak kenangan dan emosi, menjadi medan magnet yang menghubungkan jiwa sang pengamat dengan subjek yang tak lagi bernyawa.
Dengan judul ini, Barthes menyusun meditasi mendalam tentang makna dan esensi fotografi. Fotografi, baginya, adalah ruang di mana kita berdiri di antara yang nyata dan yang fana, merasakan kehadiran yang tertinggal di belakang, seakan foto-foto itu memantulkan terang yang halus dari realitas yang pernah ada, namun kini telah hilang.
Camera Lucida bukan -lagi- hanya tentang gambar yang ditangkap, tetapi tentang dampak fotografi yang menggetarkan: sebuah wahana yang membawakan kehadiran dan ketidakhadiran, hidup dan kematian, dalam kerangka waktu yang tak pernah berhenti.
“Seolah-olah Foto selalu membawa referennya bersama dirinya, keduanya dipengaruhi oleh keintiman atau kebekuan kematian yang sama, di tengah-tengah dunia yang bergerak: mereka terikat bersama, dahan demi dahan, seperti seorang terhukum dan mayat dalam penyiksaan tertentu; atau bahkan seperti pasangan ikan (hiu, menurut Michelet) yang berlayar bersama, seolah-olah disatukan oleh sebuah hubungan abadi.” (diterjemahkan dari Camera Lucida, hal 5-6)
Roland Barthes, dalam renungan ini, mengangkat sebuah wacana yang menggetarkan tentang keintiman yang mendalam antara foto dan subjeknya – atau, dalam istilahnya, “referen.”
Baginya, foto adalah medium yang menyimpan lebih dari sekadar citra; ia adalah kapal bagi jiwa, sekeping “kehadiran” dari objek yang pernah hidup di dunia nyata.
Sesaat setelah objek itu diabadikan, foto dan objeknya terjerat dalam hubungan yang tak terpisahkan, bagai dua kekasih yang saling merengkuh dalam kebisuan yang penuh kasih, atau mungkin dalam kebekuan yang menyerupai kematian. Dalam kekakuan yang abadi itu, mereka terikat erat, tak terlepaskan. Penggambaran Barthes mengenai hubungan foto dan objeknya ini memanglah gelap dan mengusik, sangat Barthesian.
Barthes membayangkan foto dan objeknya bagai dua entitas yang tersandera dalam siksa abadi, terkunci dalam posisi yang sama, tak dapat lari. Ada kesunyian yang berat dalam hubungan ini, sebuah perasaan terjepit antara hidup dan mati.
Bahkan, Barthes melukiskannya seperti sepasang ikan hiu yang melaju bersama, berenang dalam arus yang sama, berdekatan selalu, seolah-olah terikat oleh janji yang tak akan pernah terpatahkan.
Di balik kata-katanya yang puitis, Barthes merumuskan bahwa foto bukanlah sekadar “cerminan” objek; ia adalah wadah bagi esensi yang hidup, seolah jiwa objek itu tersimpan di balik kertas atau layar. Terpenjara di balik bingkai atau frame.
Setiap kali kita menatap foto, objek yang tergambar di sana seakan hadir kembali, meski ia mungkin telah lama pergi dari dunia. Di sinilah kekuatan foto berakar—bukan hanya pada citranya, melainkan pada kemampuan magisnya untuk memanggil kembali kehadiran yang telah hilang, menghadirkan rasa yang mengguncang antara ada dan tiada, hingga kita tak hanya melihat representasi, melainkan merasakan denyut kehidupan yang pernah bersemayam di dalamnya. *
Meneroka Ranah Pemikiran Barthes pada Matra Seni
Roland Barthes, kerap kali melandaskan pemikirannya pada seni. Termasuk fotografi yang ditumpahkannya dalam Camera Lucida. Barthes menggunakan perbandingan dengan seni rupa semisal lukisan dan seni peran seperti teater untuk menggali lebih dalam esensi filosofis fotografi.
Barthes melihat fotografi sebagai sesuatu yang menangkap dan “membekukan” momen kehidupan, tetapi pada saat yang sama, ia juga membawa aspek kematian. Seperti halnya teater yang sering kali menghadirkan tema kehidupan dan kematian secara dramatis, fotografi menurut Barthes juga memiliki “sentuhan kematian” karena mengabadikan momen yang berlalu dan tidak akan pernah kembali.
Bagi Barthes, setiap foto adalah momen yang tak terulang, jejak kehidupan yang langsung, namun sekaligus simbol dari ketidakhadirannya, atau kematiannya.
Di lain sisi, lukisan adalah representasi realitas yang bersifat interpretatif; pelukis mengolah, memilih, dan menambahkan subjektivitas dalam karya mereka. Sementara itu, fotografi, menurut Barthes, adalah cerminan langsung dari realitas. Foto bukanlah interpretasi, melainkan dokumentasi, sehingga objek yang ada di dalam foto memang “pernah ada di sana.”
Barthes menekankan bahwa fotografi memiliki hubungan yang lebih mendalam dengan realitas daripada lukisan, karena sifatnya yang mengabadikan apa yang nyata. Di sini, Barthes ingin membedakan fotografi dari seni yang mengandalkan proses kreatif, seperti lukisan.
Barthes menyamakan fotografi dengan teater karena keduanya memiliki elemen presentasi yang intens. Dalam teater, aktor merepresentasikan kehidupan dalam bentuk dramatis yang langsung dan nyata. Fotografi, meskipun statis, juga menyajikan momen kehidupan secara langsung, dengan menghadirkan subjek seolah-olah masih ada.
Inilah yang disebut Barthes sebagai punctum, sebuah elemen dalam foto yang “menusuk” hati penontonnya, seperti bagaimana akting di teater dapat menggetarkan hati penonton. Menurut Barthes, foto menampilkan realitas dengan “ketelanjangan” yang mirip dengan teater, meski tanpa pergerakan.
Dalam fotografi, Barthes melihat aspek teater yang “diam” atau “beku.” Foto-foto menangkap momen yang tidak bergerak tetapi masih memiliki elemen dramatis yang kuat. Seperti dalam teater, di mana adegan atau ekspresi tertentu dapat menyampaikan emosi mendalam tanpa kata-kata, foto juga dapat mengekspresikan kisah atau perasaan yang mendalam melalui komposisi, ekspresi wajah, atau latar. Ini membuat fotografi, dalam pandangan Barthes, lebih mirip dengan teater daripada seni visual lainnya, karena mampu menyampaikan “ketegangan” emosional tanpa gerak atau kata.
Barthes juga berusaha untuk memahami esensi atau hakikat fotografi dengan mengacu pada kategori ontologis seni yang sudah ada. Dalam seni rupa dan teater, pemahaman tentang apa itu realitas dan bagaimana cara terbaik merepresentasikannya adalah isu filosofis utama.
Dengan membandingkan fotografi dengan lukisan dan teater, Barthes menelusuri karakter ontologis fotografi sebagai seni yang unik. Ia mempertanyakan, misalnya, apakah fotografi hanyalah “reproduksi mekanis” pada mekanika ranah, diafragma, intensitas cahaya, dan sudut lensa? Atau lebih dari itu, sebagai sebuah jendela menuju realitas yang pernah ada.
Berangkat dari pertanyaan itu, Barthes ingin menggarisbawahi bahwa fotografi adalah seni yang memiliki hubungan unik dengan waktu, kehidupan, dan kematian. Ia melihat fotografi sebagai seni yang lebih dekat dengan kenyataan sehari-hari, dan karena itu, juga lebih dekat dengan tema-tema eksistensial yang mendalam, seperti kematian dan ketidakhadiran. (Darmadi H. Tariah)
BACA JUGA: Membaca Camera Lucida, Roland Barthes (1)